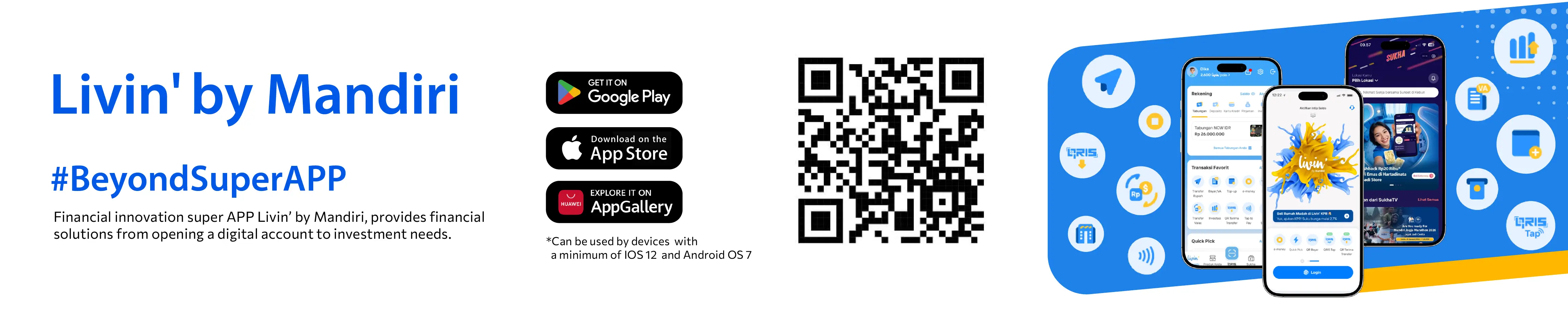Apa Maksud dari Performative Male, Maskulin Sehat atau Toxic?

ThePhrase.id – Belakangan ini media sosial khususnya TikTok diramaikan oleh istilah performative male. Tren yang menjadi wadah bagi laki-laki untuk mengekspresikan diri ini, memunculkan beragam opini dari warganet yang mempertanyakan apakah fenomena ini termasuk maskulinitas yang toxic atau sehat.
Awal mula Tren ini mencuat ketika banyak laki-laki tampil dengan gaya khas yang memadukan citra maskulin, namun dengan sentuhan “lembut” dan intelektual. Fenomena ini juga beriringan dengan meningkatnya popularitas matcha sebagai bagian dari gaya hidup, di mana minuman ini sering dikaitkan dengan femininitas.
Gaya khas yang dimaksud merujuk pada laki-laki yang mengenakan kaus vintage, celana baggy, membawa buku bertema feminisme, dan menenteng segelas matcha di tangan. Lalu apa hubungannya dengan sebutan performative male?
Sebelum mendalami maksud dari performative male, perlu diketahui bahwa pada dasarnya laki-laki tradisional atau maskulinitas yang selama ini dikonstruksikan adalah yang berperilaku kuat, dominan, dan tidak emosional serta berbanding terbalik dari karakteristik feminin yang lembut.
Sedangkan dalam tren performative male, laki-laki tampil tak mengikuti maskulinitas tradisional. Mereka justru tampil sebagai laki-laki yang lembut. Menurut Urban Dictionary, performative male adalah sesorang yang tampil sebagai ‘nice guy’ atau laki-laki baik yang berusaha untuk membawakan dirinya lebih feminin agar terlihat menarik bagi perempuan.
Dengan kata lain, para laki-laki ini menampilkan variasi maskulinitas yang disesuaikan dengan perspektif perempuan tentang laki-laki yang menarik.
Secara tidak langsung, tren performative male menunjukkan performa laki-laki di ruang publik yang disesuaikan dengan ekspektasi audiens, dalam hal ini, perempuan yang memandang laki-laki sejati sebagai sosok yang tidak takut mengekspresikan sisi femininnya.
Konsep ini berakar pada teori gender performativity (performa gender) dari filsuf Judith Butler, yang menyatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang dimiliki secara alami, tapi sesuatu yang dijalankan atau "dilakukan" secara berulang sesuai norma sosial.
Dalam konteks ini, performative male termasuk performa gender. Sehingga perilaku maskulin tersebut diadopsi bukan karena autentisitas, melainkan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang terus dikonstruksikan sehingga menciptakan realitas maskulinitas yang tampak alami padahal adalah performa.
Selain menampilkan aspek estetika dan kelembutan, performative male juga kerap disandingkan dengan gaya hidup modern pria muda yang menonjolkan "sensitivitas" dan sedikit melekat pada budaya pop seperti musik indie dan literatur feminis. Contoh selebritas yang sering dijadikan contoh adalah Timothée Chalamet dan Paul Mescal, yang berperan sebagai karakter pria yang lebih emosional dan berbeda dari stereotip maskulinitas tradisional.
Namun, meski tampak progresif dan membuka ruang ekspresi emosional pria, banyak kritik menyatakan bahwa di balik penampilan tersebut masih terdapat keinginan “maskulinitas tradisional” yang sama, yaitu, untuk mengontrol, mencari validasi, dan status sosial.
Performative male sebenarnya dinilai sebagi performa palsu atau pura-pura yang bertujuan lebih pada citra yang dilihat oleh orang lain daripada perubahan karakter yang sejati. Mereka menggunakan berbagai simbol budaya yang dekat dengan selera perempuan modern, namun motivasi utama adalah untuk memanipulasi persepsi sosial agar lebih diterima dan dianggap menarik.
Namun, berdasarkan teori, performativity oleh Judith Butler, peforma dapat dilakukan oleh siapa pun dan tidak berdasarkan gender. Maka tampil sebagai performative male tak secara alami merupakan maskulinitas yang toxic
Performa gender ini dapat menjadi toxic ketika terdapat motivasi lain seperti memanipulasi atau perliaku negative lainnya. Maka dari itu, laki-laki tetap bisa mengekspresikan diri dengan bebas dalam bentuk apapun termasuk dalam tren performative male. [Syifaa]