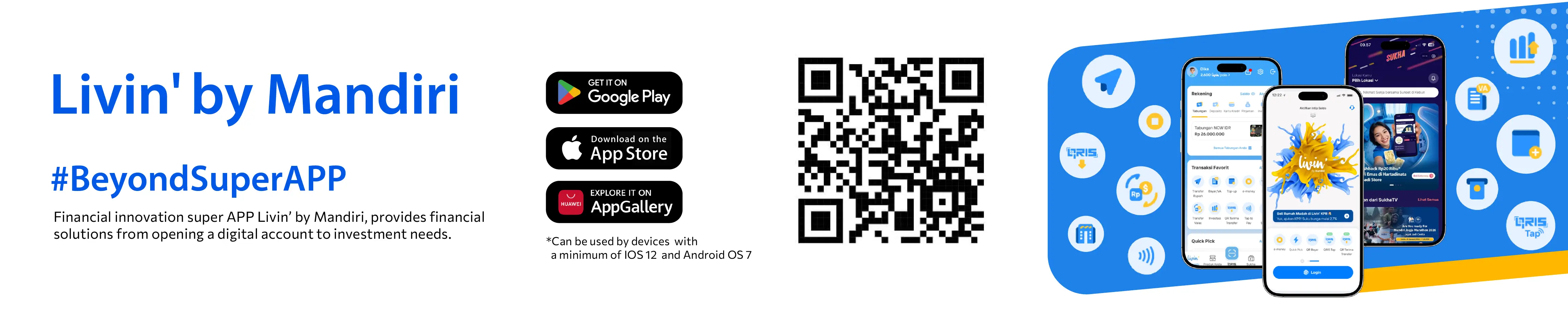Emotional Monitoring, Pola Perhatian yang Bisa Menjadi Toxic dalam Hubungan

ThePhrase.id - Dalam hubungan romantis, perhatian terhadap emosi pasangan kerap dianggap sebagai bentuk kepedulian. Namun, ada perilaku yang sering luput disadari dan justru berpotensi merusak hubungan, yaitu emotional monitoring. Istilah ini menggambarkan kebiasaan terus-menerus mengamati, menafsirkan, dan mengantisipasi emosi orang lain, terutama pasangan, demi menjaga rasa aman atau menghindari konflik.
Perilaku ini berbeda dari empati yang sehat. Emotional monitoring membuat seseorang sangat peka terhadap perubahan kecil pada suasana hati pasangan, seperti nada bicara, ekspresi wajah, atau sikap yang terlihat tidak biasa. Tujuannya sering kali bukan sekadar memahami, melainkan mengendalikan situasi agar tidak terjadi ketegangan. AO Psychology menjelaskan bahwa pola ini kerap berkembang sebagai mekanisme koping, terutama pada individu yang tumbuh di lingkungan emosional yang tidak stabil atau penuh tekanan, sehingga mereka belajar membaca emosi orang lain sebagai cara bertahan.
Dalam tahap awal hubungan, emotional monitoring sering terlihat seperti perhatian berlebih. Seseorang mungkin merasa dirinya pasangan yang suportif karena selalu berusaha menenangkan, menyesuaikan diri, dan menghindari hal-hal yang bisa memicu emosi negatif. Namun, seiring waktu, pola ini bisa menciptakan ketimpangan peran, di mana satu pihak menjadi pengelola emosi, sementara pihak lain tanpa sadar menjadi objek yang terus diamati.
Verywell Mind menyoroti bahwa emotional monitoring dapat berubah menjadi toxic ketika seseorang merasa bertanggung jawab penuh atas perasaan pasangannya. Individu yang melakukan emotional monitoring cenderung mengabaikan kebutuhan emosional dirinya sendiri demi menjaga stabilitas hubungan. Akibatnya, muncul kelelahan emosional, kecemasan kronis, dan rasa takut berlebihan terhadap konflik, bahkan untuk hal-hal kecil.
Dampak negatifnya juga dirasakan oleh pasangan yang dimonitor. Mereka bisa merasa tidak bebas mengekspresikan emosi secara jujur karena khawatir reaksi mereka akan dianalisis atau “diperbaiki.” Hubungan pun kehilangan ruang aman untuk mengalami emosi secara alami, baik itu sedih, marah, maupun kecewa. AO Psychology menyebut kondisi ini sebagai bentuk hypervigilance yang berkepanjangan dan tidak sehat bagi kedua belah pihak.
Dalam jangka panjang, emotional monitoring yang tidak disadari dapat mengaburkan batas antara peduli dan mengontrol. Hubungan menjadi dipenuhi asumsi, bukan komunikasi terbuka. Alih-alih bertanya langsung dan memberi ruang bagi pasangan untuk mengelola emosinya sendiri, emotional monitoring justru menempatkan satu pihak dalam posisi terus waspada dan tertekan.
Para psikolog menekankan bahwa hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang menuntut seseorang selalu memantau emosi pasangannya, melainkan hubungan yang memungkinkan kedua individu mengekspresikan perasaan secara jujur, bertanggung jawab atas emosinya masing-masing, serta menghormati batas pribadi. Memahami emotional monitoring sebagai pola yang perlu disadari, bukan dinormalisasi, menjadi langkah penting agar hubungan tidak bergeser dari perhatian menjadi tekanan emosional yang merusak. (Syifa)