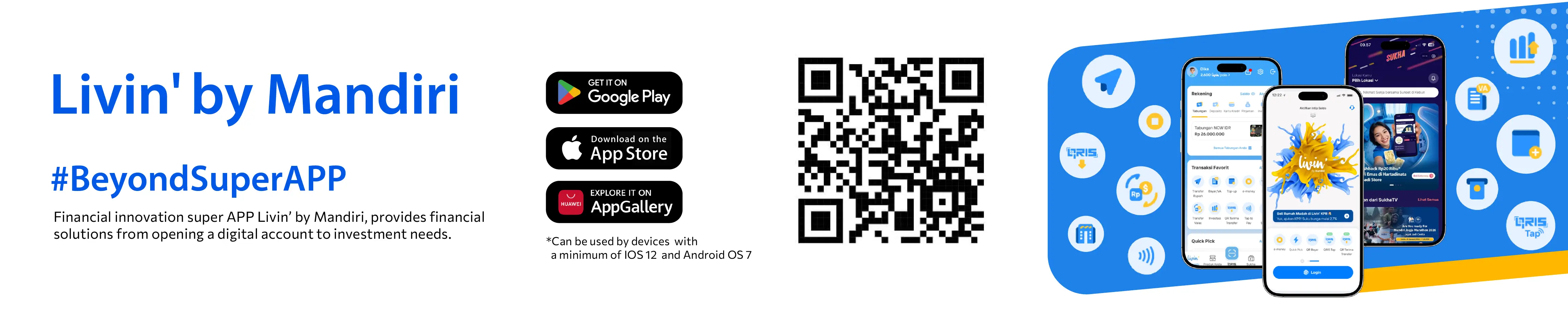Iran, Inflasi, dan Kebuntuan Rezim

ThePhrase.id - Dalam beberapa dekade terakhir, republik Islam ini telah terbiasa hidup di bawah sanksi, tekanan internasional, dan isolasi ekonomi. Namun, ketika nilai mata uang nasional, rial, terjun bebas secara brutal, kesabaran sosial yang selama ini direkatkan oleh represi, subsidi, dan retorika revolusioner akhirnya retak. Bukan karena rakyat tiba-tiba tercerahkan secara ideologis, melainkan karena hidup sehari-hari menjadi tak lagi masuk akal.
Penurunan tajam nilai tukar bukan sekadar statistik makroekonomi. Ia adalah pengalaman kolektif yang konkret: harga roti melonjak, tabungan menguap, upah menjadi tak berguna, dan masa depan kehilangan bentuk. Dalam konteks seperti ini, protes tidak lahir dari pamflet atau manifesto, melainkan dari antrean panjang di toko dan layar ponsel yang setiap hari memperlihatkan nilai rial yang terus runtuh. Politik, dalam arti paling telanjang, kembali menjadi urusan perut.
Rezim Iran selama ini mengklaim legitimasi dari kombinasi agama, nasionalisme anti-Barat, dan narasi perlawanan. Namun inflasi adalah bahasa yang tidak mengenal ideologi. Ketika harga melonjak di luar kendali, klaim moral negara runtuh dengan sendirinya. Negara boleh berbicara tentang martabat Islam dan kedaulatan nasional, tetapi warga yang tak mampu membeli kebutuhan dasar akan membaca itu sebagai sinisme.
Dalam teori politik klasik, krisis ekonomi jarang otomatis melahirkan revolusi. Tetapi ia hampir selalu merusak legitimasi. Iran hari ini menunjukkan pola itu secara telanjang. Pemerintah mencoba menyalahkan sanksi Barat, spekulan, atau “musuh revolusi”. Namun narasi tersebut makin kehilangan daya ketika rakyat melihat elite politik dan militer tetap hidup nyaman, bahkan diuntungkan oleh sistem ekonomi yang kacau.
Di sinilah inflasi berubah dari masalah teknis menjadi krisis politik. Ia memperlihatkan bahwa negara tidak lagi mampu menjalankan fungsi dasar: melindungi nilai kerja warganya. Dalam negara yang mengklaim diri sebagai “Republik Islam”, kegagalan ini bukan hanya administratif, tetapi juga teologis.
Gelombang protes yang muncul akibat kejatuhan mata uang awalnya tampak banal. Teriakan soal harga, upah, dan pengangguran mendominasi. Namun sejarah menunjukkan bahwa protes ekonomi jarang berhenti pada tuntutan ekonomi. Begitu massa turun ke jalan dan aparat mulai represif, tuntutan melebar. Dari harga roti ke harga kekuasaan.
Iran mengikuti skrip ini dengan disiplin yang hampir akademik. Demonstrasi yang dimulai di kota-kota kecil dan pasar tradisional dengan cepat menyebar ke pusat-pusat urban. Para pedagang, buruh, mahasiswa, dan kelas menengah yang tergerus inflasi menemukan musuh bersama: negara yang tak kompeten sekaligus tak mau mengaku gagal.
Namun yang menarik, protes ini tidak memiliki pusat ideologis yang jelas. Tidak ada tokoh karismatik, tidak ada manifesto revolusioner, tidak ada partai oposisi yang terorganisasi. Ini adalah protes era modern: cair, sporadis, dan emosional. Kekuatan sekaligus kelemahannya terletak di situ.
Respon negara terhadap protes mengikuti pola lama: represi cepat, sensor informasi, dan kriminalisasi ketidakpuasan. Aparat keamanan digerakkan, media sosial dibatasi, dan bahasa kekuasaan kembali mengeras. Negara bertindak seolah stabilitas dapat dipulihkan dengan kekerasan administratif.
Namun ada ironi yang tak bisa ditutupi. Negara yang terlalu cepat memukul menunjukkan ketakutannya sendiri. Rezim Iran memahami bahwa krisis ekonomi yang dalam adalah bahan bakar paling berbahaya bagi oposisi, bahkan yang tidak terorganisasi. Dalam istilah ilmu politik, ini adalah “legitimacy shock”, guncangan legitimasi yang sulit dipulihkan hanya dengan paksaan.
Represi memang efektif dalam jangka pendek. Jalanan bisa dikosongkan, suara bisa dibungkam. Tetapi harga politiknya mahal: setiap pemukulan memperdalam jarak antara negara dan masyarakat. Negara berhenti menjadi pelindung, berubah menjadi predator.
Selama bertahun-tahun, kelas menengah Iran berfungsi sebagai penyangga stabilitas. Mereka tidak sepenuhnya loyal, tetapi cukup rasional untuk menghindari konfrontasi terbuka. Namun inflasi ekstrem dan depresiasi mata uang menghancurkan posisi ini. Ketika kelas menengah mulai jatuh miskin, mereka kehilangan insentif untuk mempertahankan status quo.
Dalam banyak rezim otoriter, kelas menengah adalah aktor penentu: terlalu makmur untuk memberontak, terlalu cerdas untuk sepenuhnya tunduk. Iran hari ini menunjukkan apa yang terjadi ketika kelompok ini didorong ke tepi jurang ekonomi. Mereka menjadi politis bukan karena ideologi, tetapi karena kehilangan segalanya yang membuat kompromi masuk akal.
Rezim Iran sangat bergantung pada narasi eksternal: musuh di luar negeri, konspirasi Barat, dan sanksi sebagai bukti ketidakadilan global. Namun narasi ini memiliki batas daya tahan. Ketika krisis berlangsung terlalu lama, rakyat mulai bertanya: jika semua ini demi perlawanan, mengapa yang menderita selalu mereka?
Di titik ini, nasionalisme defensif berubah menjadi bahan bakar sinisme. Rakyat tidak lagi marah pada Barat, tetapi pada elite domestik yang menggunakan konflik eksternal sebagai pembenaran kegagalan internal. Dalam bahasa politik, legitimasi ideologis runtuh ketika biaya sosialnya tak lagi dapat ditanggung.
Meski meluas dan intens, protes di Iran belum menjelma menjadi revolusi. Negara masih utuh, elite masih solid, dan oposisi masih terfragmentasi. Ini menegaskan satu pelajaran pahit dalam ilmu politik: penderitaan ekonomi tidak otomatis menghasilkan perubahan rezim.
Namun kesimpulan sebaliknya juga berbahaya. Ketika negara kehilangan kemampuan ekonomi dan moral sekaligus, ia memasuki fase erosi kronis. Rezim mungkin bertahan, tetapi dengan biaya stabilitas jangka panjang yang semakin tinggi. Setiap krisis baru akan lebih sulit dikelola.
Kejatuhan nilai tukar di Iran bukan sekadar episode ekonomi, melainkan gejala penyakit politik yang lebih dalam: negara yang terjebak antara ideologi usang dan realitas global yang tak bisa dinegosiasikan. Protes yang muncul adalah tanda peringatan, bukan klimaks.
Pelajaran dari Iran jelas namun tidak romantis. Rakyat yang marah belum tentu revolusioner. Negara yang represif belum tentu runtuh. Tetapi ketika ekonomi gagal total, semua rezim, bahkan yang paling ideologis akan kehilangan fondasi paling dasar: kemampuan membuat hidup warganya masuk akal.
Ketika hidup tak lagi masuk akal, politik berhenti menjadi soal loyalitas. Ia berubah menjadi soal bertahan hidup. Di situlah, sejarah biasanya mulai bergerak meski pelan, tidak heroik, tetapi tak mungkin terelakkan.