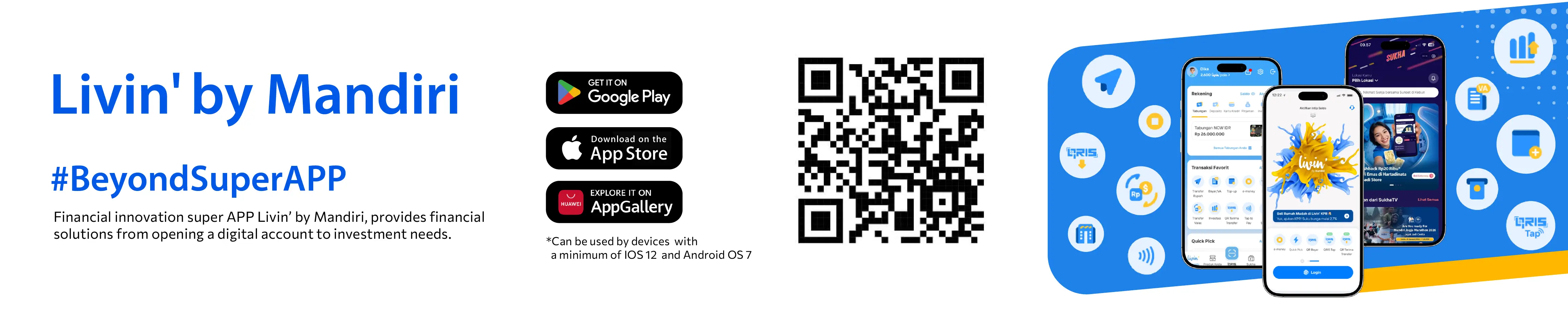Ketika Efisiensi Menjadi Dalih: Pilkada Tak Langsung sebagai Proyek Eksklusi Politik

ThePhrase.id - Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung dan pengembalian mekanismenya kepada DPRD bukanlah sekadar perdebatan teknis tentang tata kelola pemilu. Ia adalah ekspresi telanjang dari konflik kelas dalam demokrasi Indonesia kontemporer, konflik yang berusaha disamarkan melalui bahasa netral kebijakan publik.
Di balik retorika efisiensi, stabilitas, dan penghematan anggaran, tersembunyi satu kegelisahan lama elite politik: demokrasi yang terlalu partisipatoris selalu membawa risiko politik bagi mereka yang telah mapan. Dalam sejarah politik modern, setiap kali demokrasi dinyatakan “terlalu mahal”, yang sesungguhnya dipersoalkan bukan biaya fiskal, melainkan biaya ketidakpastian kekuasaan.
Terlalu banyak pemilih berarti terlalu banyak variabel yang tak bisa dikendalikan. Terlalu banyak partisipasi berarti terlalu banyak suara yang berpotensi menyimpang dari konsensus elite. Pilkada langsung, dalam kerangka ini, bukan persoalan administratif, melainkan gangguan struktural terhadap konsolidasi kekuasaan oligarkis di tingkat lokal.
Joseph Schumpeter yang sering dibaca sebagai pembela demokrasi minimalis, setidaknya masih mengakui satu prinsip dasar: demokrasi adalah mekanisme kompetisi elite untuk memperebutkan suara rakyat. Bahkan dalam versi paling minimal sekalipun, rakyat tetap berfungsi sebagai arbiter terakhir. Namun apa yang terjadi ketika kompetisi itu dikeluarkan dari hadapan rakyat dan dipersempit menjadi negosiasi antar-elite?
Pilkada tak langsung mengakhiri bahkan standar minimal Schumpeterian. Ia mengubah demokrasi dari kompetisi terbuka menjadi kartel politik, di mana jabatan eksekutif daerah didistribusikan melalui kompromi intra-partai, lobi modal, dan disiplin fraksi, bukan melalui pertarungan gagasan di ruang publik.
Dari sudut pandang kiri-kritis, ini bukan penyimpangan, melainkan logika normal demokrasi kapitalistik yang memasuki fase defensif. Ketika ketimpangan ekonomi memburuk, kapasitas negara tergerus oleh logika pasar, dan legitimasi partai politik runtuh, elite cenderung menutup ruang politik alih-alih membukanya. Demokrasi tetap dipertahankan sebagai simbol prosedural, tetapi isinya dikosongkan dari partisipasi substantif.
Robert Dahl, melalui konsep polyarchy, menekankan bahwa demokrasi modern mensyaratkan dua elemen kunci: kontestasi yang bermakna dan partisipasi yang inklusif. Pilkada langsung, betapapun cacat, mahal, dan sarat uang, masih menyediakan keduanya. Ia membuka ruang bagi kompetisi relatif terbuka dan memberi rakyat hak untuk ikut menentukan siapa yang memerintah mereka.
Pilkada tak langsung, sebaliknya, adalah mekanisme sistematis untuk memutus partisipasi kelas bawah dari proses pengambilan keputusan politik. Rakyat tetap dipanggil sebagai sumber legitimasi simbolik, tetapi dikeluarkan dari arena penentuan kekuasaan yang nyata. Ini bukan sekadar pengurangan hak pilih, melainkan restrukturisasi hubungan antara negara dan warga.
Pendukung pilkada tak langsung kerap berargumen bahwa DPRD adalah representasi rakyat, sehingga mekanisme ini tetap demokratis. Klaim ini sah secara formal, tetapi rapuh secara material. DPRD bukan ruang representasi netral, melainkan arena dominasi partai dan modal. Rekrutmen kandidat dikontrol elite partai, pendanaan politik bergantung pada oligarki ekonomi, dan disiplin fraksi secara sistematis menundukkan kepentingan konstituen.
Menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD berarti menyerahkan kekuasaan eksekutif lokal kepada koalisi oligarki partai dan pemilik modal. Dalam kerangka ekonomi-politik, pilkada tak langsung adalah bentuk akumulasi kekuasaan melalui eksklusi politik. Semakin sedikit aktor yang terlibat dalam proses pemilihan, semakin rendah biaya transaksi politik bagi elite.
Politik uang tidak dihapus tetapi disederhanakan. Dari ratusan ribu pemilih menjadi puluhan legislator. Dari arena publik ke ruang tertutup. Dari risiko sosial menjadi risiko internal. Inilah rasionalitas neoliberal dalam praktik politik: mengurangi kompleksitas demokrasi agar selaras dengan logika efisiensi elite.
Argumen bahwa pilkada langsung “terlalu mahal” juga menyimpan bias kelas yang tajam. Demokrasi dianggap mahal karena ia memberi ruang tawar bagi rakyat miskin: ruang yang dianggap mengganggu stabilitas dan kepastian kebijakan. Namun demokrasi tidak pernah dianggap mahal ketika negara mengucurkan insentif kepada korporasi besar, menyelamatkan konglomerasi bermasalah, atau membiarkan kebocoran anggaran melalui korupsi struktural.
Dalam logika neoliberal, partisipasi rakyat adalah satu-satunya pengeluaran yang selalu ingin dipangkas. Demokrasi direduksi menjadi persoalan manajemen, bukan konflik kepentingan. Warga diposisikan sebagai pengguna layanan, bukan subjek politik. Inilah yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai demokrasi pasca-politik: kondisi di mana konflik ideologis disingkirkan demi konsensus teknokratis.
Pilkada tak langsung adalah manifestasi konkret dari pasca-politik itu. Konflik kelas, konflik kepentingan, dan konflik ideologis dipindahkan dari ruang publik ke ruang elite. Politik direduksi menjadi urusan tata kelola, bukan pertarungan visi tentang distribusi kekuasaan dan sumber daya. Elite menyebut ini stabilitas; pertanyaannya dalam bahasa kiri-kritis, ini adalah stabilitas untuk siapa?
Stabilitas bagi elite sering berarti stagnasi bagi rakyat. Ketika konflik disingkirkan dari ruang publik, ia tidak lenyap; ia menumpuk. Demokrasi yang menolak konflik tidak menjadi harmonis, melainkan rapuh. Sejarah menunjukkan bahwa represi konflik atas nama efisiensi sering kali melahirkan ledakan politik yang jauh lebih destruktif.
Demokrasi modern jarang mati secara dramatis. Ia mati pelan-pelan, melalui perubahan prosedural yang sah secara hukum tetapi merusak secara politik. Di lain pihak, proses ini sering dianggap sebagai 'democratic erosion': pelemahan bertahap norma dan praktik demokrasi tanpa pembatalan formal institusinya. Pilkada tak langsung adalah contoh klasik dari proses tersebut.
Tidak ada tank di jalan, tidak ada pembubaran parlemen. Namun satu demi satu hak politik dipersempit dengan alasan rasional, legal, dan terdengar masuk akal. Demokrasi direduksi menjadi ritual elektoral tanpa risiko bagi elite.
Dari perspektif historis, ini adalah bentuk counter-reformasi demokratis. Reformasi 1998 membuka ruang partisipasi rakyat sebagai koreksi atas konsentrasi kekuasaan Orde Baru. Dua dekade kemudian, ketika ruang itu mulai mengganggu kenyamanan elite baru, muncul dorongan untuk menutupnya kembali. Sejarah tidak berulang secara identik, tetapi logika kelasnya tetap sama.
Penolakan publik terhadap pilkada tak langsung sejak 2014 hingga kini menunjukkan bahwa kesadaran politik rakyat jauh lebih maju daripada asumsi elite. Rakyat memahami bahwa pilkada langsung bukan sekadar mekanisme memilih kepala daerah, melainkan simbol hak untuk ikut menentukan arah kekuasaan lokal.
Gerakan-gerakan sipil yang muncul bukan respons emosional sesaat, melainkan ekspresi rasional dari pengalaman historis: setiap kali rakyat disingkirkan dari politik, yang menguat adalah korupsi, ketimpangan, dan kekerasan struktural. Dalam kerangka teori kritis, pilkada langsung adalah ruang kontradiktif, ia memungkinkan kooptasi oligarki, tetapi juga membuka celah resistensi.
Karena itulah pilkada langsung dianggap berbahaya. Bukan karena ia gagal, tetapi karena ia masih membuka kemungkinan koreksi dari bawah. Reformasi pendanaan politik, demokratisasi internal partai, dan pembatasan peran modal adalah agenda yang terlalu radikal bagi elite. Jauh lebih mudah mencabut hak pilih rakyat daripada membongkar struktur kekuasaan sendiri.
Pada titik ini, wacana pilkada tak langsung tidak lagi bisa dibaca sebagai kebijakan netral. Ia adalah proyek politik kelas untuk mengamankan kekuasaan elite dalam situasi krisis legitimasi. Demokrasi dipertahankan sebagai simbol prosedural, tetapi rakyat dikeluarkan dari substansinya.
Menolak pilkada tak langsung, dengan demikian, bukan sikap romantik atau populis, melainkan posisi kritis yang konsisten: membela demokrasi sebagai ruang konflik terbuka, bukan sebagai administrasi kekuasaan. Demokrasi tanpa rakyat bukan demokrasi; ia hanyalah manajemen oligarki dengan wajah prosedural.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali elite mencoba menghemat demokrasi, yang terjadi justru pemborosan krisis. Republik ini pernah membayar mahal untuk stabilitas semu. Mengulanginya kali ini dengan bahasa efisiensi, tata kelola, dan netralitas teknokratis bukanlah kemajuan. Ia adalah regresi yang disamarkan sebagai rasionalitas.