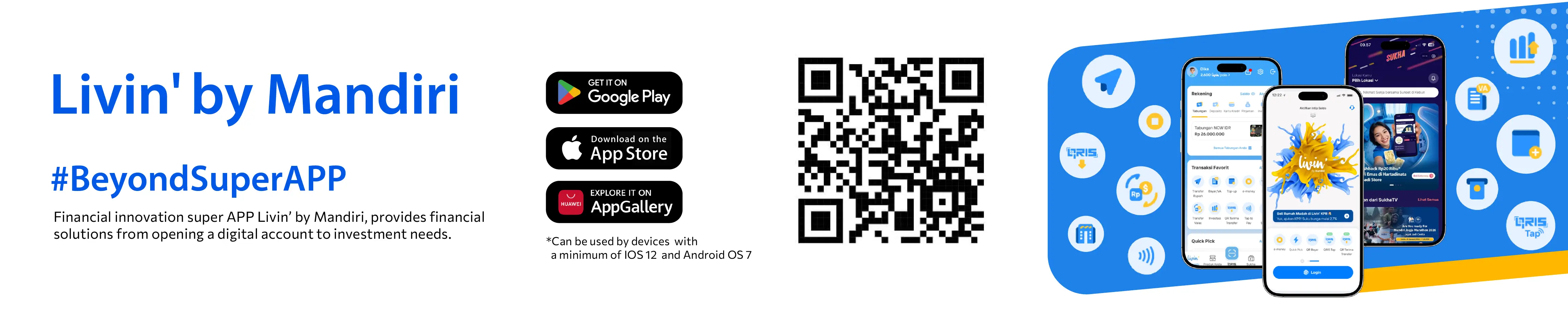Pilkada Tak Langsung dan Krisis Representasi Politik

ThePhrase.id - Ada ironi yang terlalu telanjang untuk diabaikan. Ketika banjir menenggelamkan Sumatra, mengulangi siklus kegagalan negara dalam mengelola risiko ekologis, sebagian elite politik Indonesia justru sibuk mendiskusikan cara menenggelamkan satu capaian penting Reformasi: pemilihan kepala daerah secara langsung. Seolah problem bangsa ini bukan lemahnya kapasitas negara, rendahnya akuntabilitas birokrasi, atau krisis legitimasi kebijakan publik, melainkan terlalu banyak rakyat yang ikut memilih.
Wacana pilkada tidak langsung, yang kini didorong secara terbuka oleh koalisi partai-partai besar di parlemen, bukan sekadar soal desain teknokratis demokrasi. Ia adalah gejala ideologis: sebuah kerinduan laten pada politik keteraturan semu ala Orde Baru, dibungkus dengan bahasa efisiensi, stabilitas, dan penghematan anggaran.
Seperti biasa, dalih rasional dipakai untuk menutupi hasrat lama: mengendalikan kekuasaan dengan meminggirkan rakyat.
Bahwa empat partai—Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB—yang secara kumulatif menguasai lebih dari separuh kursi DPR, bersedia mendorong agenda ini, seharusnya membuat kita berhenti berpura-pura.
Ini bukan wacana pinggiran. Ini adalah ancaman serius terhadap arsitektur demokrasi pasca-1998. Jika paripurna digelar hari ini, pilkada langsung bisa saja tinggal catatan kaki sejarah. Demokrasi, dalam skenario ini, direduksi menjadi prosedur internal elite, bukan relasi antara rakyat dan kekuasaan.
Argumen bahwa pilkada langsung adalah “warisan Reformasi” sering diperlakukan sebagai slogan normatif. Padahal, secara historis dan konstitusional, ia lebih dari itu. Pilkada langsung adalah koreksi struktural terhadap sistem politik sentralistik Orde Baru, yang memutus mata rantai pertanggungjawaban kepala daerah kepada warga.
Dalam sistem lama, loyalitas kepala daerah mengalir ke atas, kepada presiden dan elite pusat bukan ke bawah, kepada rakyat. Reformasi membalik arah arus itu, dengan satu asumsi mendasar: kekuasaan hanya sah jika dipinjam langsung dari warga.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tidak menyisakan ruang abu-abu: kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan di tangan partai, bukan di ruang lobi DPRD, dan tentu bukan di meja makan elite.
Ketika pemilihan kepala daerah dialihkan kembali ke DPRD, yang terjadi bukan sekadar perubahan mekanisme, melainkan amputasi atas prinsip kedaulatan itu sendiri. Rakyat direduksi menjadi penonton, sementara elite kembali menjadi kurator tunggal kekuasaan lokal.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Putusan No. 85/PUU-XX/2022, No. 135/PUU-XXII/2024, dan No. 110/PUU-XXIII/2025, secara konsisten menegaskan bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu yang sama dengan pemilihan presiden dan legislatif. Ini bukan tafsir pinggiran, melainkan konsensus yudisial yang memandang pilkada langsung sebagai instrumen penguatan kedaulatan rakyat.
Mengabaikan putusan-putusan ini berarti menormalisasi pembangkangan konstitusional atas nama kepentingan politik jangka pendek. Di lain pihak, para pendukung pilkada tidak langsung kerap berlindung di balik argumen biaya mahal dan politik uang. Ini argumen yang terdengar masuk akal, sampai kita menelisiknya sedikit lebih dalam.
Pertama, demokrasi memang mahal, tetapi mahal dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan biaya korupsi kebijakan, kartel politik, dan kepala daerah tanpa legitimasi publik? Biaya demokrasi adalah investasi jangka panjang pada kepercayaan publik dan stabilitas politik. Menghitungnya semata dalam neraca APBD adalah kekeliruan kategori.
Kedua, menyalahkan pilkada langsung atas maraknya politik uang adalah bentuk pengalihan tanggung jawab yang nyaris sinis. Politik uang bukan produk dari rakyat yang memilih, melainkan dari elite yang mencalonkan diri tanpa etika dan partai yang gagal atau enggan menegakkan disiplin internal.
Dalam sistem pilkada tidak langsung, praktik transaksi politik justru lebih terkonsentrasi, lebih tertutup, dan lebih murah untuk disuap. Jika politik uang dianggap masalah, memindahkan pemilihan ke ruang DPRD bukan solusi; itu hanya memindahkan pasar dari lapangan terbuka ke ruang tertutup.
Pertanyaannya sederhana tapi tidak nyaman: mengapa kesalahan partai harus dibayar dengan pencabutan hak rakyat? Jika partai gagal mendidik kader, gagal menyeleksi calon, dan gagal menghukum pelaku politik uang, mengapa justru rakyat yang dihukum dengan penghilangan hak pilih? Logika ini terbalik secara moral dan cacat secara demokratis.
Lebih dari itu, wacana pilkada tidak langsung mengabaikan satu fakta politik yang krusial: rakyat Indonesia bukan entitas pasif yang lupa sejarah. Sejak 2014, penolakan terhadap kembalinya sistem Orde Baru dalam pemilihan kepala daerah muncul berulang kali, dalam bentuk yang berbeda-beda, dengan pesan yang sama. Dari gerakan “Shame on You SBY”, Kawal Putusan MK, hingga berbagai mobilisasi sipil pada 2024 dan 2025, pesan publik konsisten: jangan rampas kedaulatan kami.
Elite politik tampaknya salah membaca kesabaran publik sebagai kepasrahan. Ini kesalahan klasik rezim-rezim yang merasa terlalu aman di atas kursi kekuasaan. Mereka lupa bahwa legitimasi demokrasi bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga soal penerimaan sosial. Pilkada tidak langsung mungkin bisa disahkan secara legal, tetapi ia akan lahir dengan cacat legitimasi sejak hari pertama.
Perlu diingat, bahwa yang lebih mengkhawatirkan adalah watak regresif dari wacana ini. Di tengah gelombang global kemunduran demokrasi, Indonesia justru sedang mempertaruhkan apakah Reformasi adalah fase transisional atau fondasi permanen. Mengembalikan pilkada ke DPRD bukan sekadar langkah mundur; ia adalah sinyal bahwa elite politik tidak lagi percaya pada rakyatnya sendiri.
Dalam narasi besar kebangsaan, demokrasi Indonesia selalu digambarkan sebagai proses “belajar sambil jalan”. Argumen ini sering dipakai untuk memaklumi kekurangan. Namun belajar bukan berarti menyerah. Ketika sistem menghadapi problem, jawabannya adalah reformasi institusi, bukan restorasi otoritarianisme. Memperbaiki pilkada langsung dengan pendanaan publik yang lebih sehat, penegakan hukum yang tegas, dan demokratisasi internal partai jauh lebih konsisten dengan semangat Reformasi dibandingkan membunuhnya secara perlahan.
Pada akhirnya, wacana pilkada tidak langsung memperlihatkan satu hal dengan sangat jelas: krisis kepercayaan elite terhadap rakyat. Di balik jargon efisiensi dan stabilitas, tersembunyi ketakutan terhadap suara publik yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Ini bukan argumen kebijakan; ini refleksi psikologi kekuasaan.
Sejarah politik Indonesia memberi pelajaran yang terlalu mahal untuk dilupakan. Stabilitas yang dibangun dengan menekan partisipasi rakyat selalu rapuh. Ia mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi menyimpan akumulasi ketegangan di bawahnya. Reformasi 1998 adalah bukti paling nyata bahwa stabilitas tanpa legitimasi hanyalah jeda sebelum krisis berikutnya.
Menolak pilkada tidak langsung, dengan demikian, bukan nostalgia Reformasi, melainkan tindakan rasional untuk menjaga masa depan demokrasi. Ini bukan soal romantisme masa lalu, tetapi soal keberanian untuk tidak kembali ke sistem yang telah terbukti gagal. Dalam politik, seperti dalam sejarah, langkah mundur jarang membawa keselamatan tetapi hanya menunda kejatuhan.