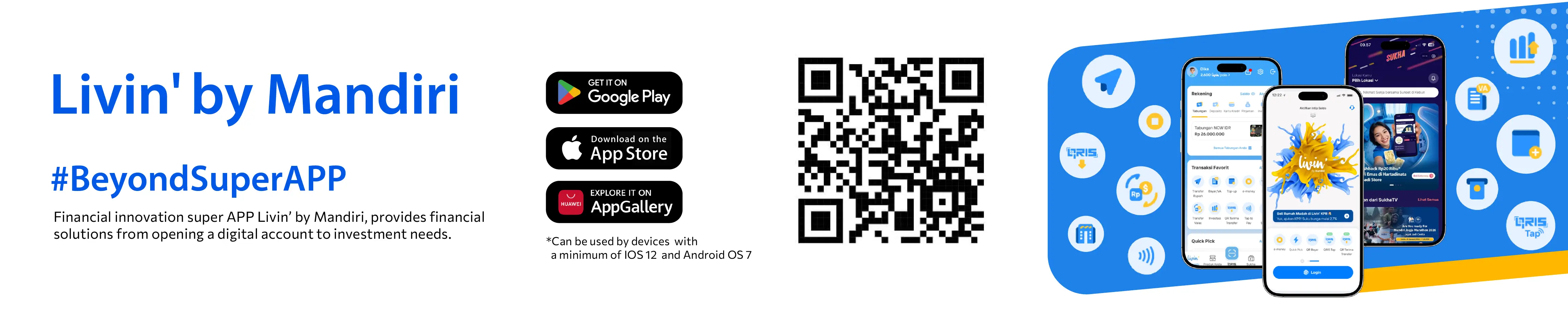Politik Ekstraksi dalam Bayang-Bayang Krisis Lingkungan

ThePhrase.id - Indonesia sering dipromosikan sebagai salah satu titik panas megabiodiversitas dunia, sebuah reputasi alamiah yang memberikan identitas ekologis global. Namun dalam dua dekade terakhir, negeri ini justru cenderung memperlakukan kekayaan ekologisnya seperti warisan yang habis pakai: diperah cepat, dijual murah, dan ditinggalkan rusak.
Hutan tropis ditebang dengan ritme industri, pesisir direklamasi tanpa kajian ekologis yang memadai, tambang dan hilirisasi nikel merangsek ke wilayah-wilayah sensitif, sementara monokultur sawit terus menelan ruang hidup lokal. Setiap musim hujan, rakyat menyaksikan akibatnya: banjir bandang, longsor, dan degradasi ekologi yang lebih sering disalahkan pada “cuaca ekstrem” ketimbang pada struktur ekonomi-politik yang mengatur bagaimana alam diperlakukan.
Jika ada satu ironi besar dalam sejarah pembangunan Indonesia modern, ia terletak pada kenyataan bahwa negara yang paling bergantung pada stabilitas ekologis justru paling agresif merusaknya. Dan ironinya memperlihatkan dirinya setiap tahun melalui statistik kebencanaan: ratusan peristiwa hidrometeorologis yang meningkat bukan karena curah hujan semakin tinggi, tetapi karena ekosistem semakin tak mampu menyerap guncangan alam. Menyebut banjir sebagai peristiwa “alamiah” sama saja dengan menyalahkan termometer atas demam yang diciptakan oleh ulah sendiri.
Dalam kerangka ekologi politik, kerusakan seperti ini tidak pernah sekadar akibat alam. Alam tidak bangun di suatu pagi dan memutuskan untuk longsor. Kerusakan adalah konsekuensi dari relasi kekuasaan yang membentuk bagaimana sumber daya dikontrol, dimanfaatkan, dan diberi makna. Di Indonesia, relasi kekuasaan ini terdiri dari oligarki ekonomi, birokrasi yang rapuh, dan narasi teknokratis yang memukau, semuanya bekerja nyaris sempurna.
Mereka menciptakan kondisi di mana eksploitasi alam bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi menjadi infrastruktur politik yang menopang akumulasi modal dan stabilitas kekuasaan. Dalam konteks ini, oligarki ekstraktif memainkan peran penting yang sering kali disamarkan oleh kabut istilah teknis. Kalangan elite bisnis-politik yang beroperasi di sektor tambang, sawit, energi fosil, dan properti pesisir tidak hanya menguasai sumber daya; mereka mengatur lanskap regulasi.
Struktur yang digambarkan oleh para ahli, dari Jeffrey Winters hingga Robison dan Hadiz, menunjukkan betapa oligarki Indonesia bersifat hibrid: bergerak di antara pusat dan daerah, menguasai sumber daya formal dan informal, serta memadukan kekuatan modal dengan jejaring politik yang lentur. Tak mengherankan jika izin tambang, konsesi hutan, dan ekspansi perkebunan sering terlihat sebagai proyek politik ketimbang semata keputusan ekonomi.
Para elite ini tidak bekerja sendirian. Dalam ekologi politik, kekuasaan tidak hanya bertahan melalui kontrol material, tetapi juga melalui kontrol pengetahuan. Di sinilah teknokrasi memainkan peran yang sering kali luput dari sorotan publik. Setiap proyek ekstraksi membutuhkan legitimasi ilmiah yang tampak objektif: laporan AMDAL yang mulus, proyeksi ekonomi yang menjanjikan, kajian teknis yang menegaskan bahwa “risiko lingkungan dapat dikendalikan”.
Namun realitas menunjukkan bahwa banyak produk pengetahuan ini diproduksi dalam kondisi 'epistemic capture', ketika lembaga pengetahuan, baik pemerintah maupun akademis, perlahan menjadi perpanjangan tangan kepentingan industri. Bahasa ilmiah kemudian berubah menjadi bahasa pembenaran. Kata-kata seperti “optimalisasi”, “nilai tambah”, dan “ketahanan energi” terdengar impresif, tetapi sering kali berfungsi seperti kosmetik bagi luka ekologis yang terbuka.
Birokrasi Indonesia, yang seharusnya menjadi penjaga gerbang keberlanjutan, justru kerap memperkuat dominasi oligarki melalui mekanisme yang halus namun sistemik. Regulasi yang kompleks dan prosedur yang panjang bukanlah jaminan perlindungan ekologis; ia sering berubah menjadi ritual administratif yang menutupi kenyataan bahwa negara lebih sibuk menyalurkan izin ketimbang mengawasi dampak.
Pemerintah daerah bergantung pada pemasukan dari sektor ekstraktif ini untuk membiayai program dan ambisi politik jangka pendek. Pemerintah pusat mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan, bahkan ketika pertumbuhan itu dibangun dengan merusak basis ekologis yang menopangnya. Dalam situasi seperti ini, regulasi lingkungan tidak menghadirkan batas; ia menghadirkan peluang interpretasi bagi mereka yang memiliki sumber daya untuk menawarnya.
Industri tambang menjadi ilustrasi paling gamblang. Indonesia kini tampil sebagai pemain global dalam nikel dan batubara, dua komoditas yang disebut sebagai motor ekonomi dan industrialisasi. Namun jejak ekologisnya jauh lebih mahal dari nilai ekspornya. Hilirisasi nikel digadang-gadang sebagai kisah sukses industrialisasi Indonesia abad ke-21, tetapi kenyataannya hilirisasi ini lebih mirip intensifikasi ekstraksi.
Ia membutuhkan energi besar, ironisnya masih ditopang batubara, menghasilkan polusi udara dan air yang signifikan, dan menciptakan limbah baru yang tidak mudah dikelola. Hutan hilang, sungai tersedimentasi, dan pesisir tercemar. Namun narasi resmi tetap memuja hilirisasi sebagai jalan emas menuju masa depan industri, seolah dampak ekologis hanyalah detail administratif yang bisa diselesaikan dalam rapat koordinasi.
Sementara itu, ekspansi sawit terus merombak struktur sosial-ekologis Indonesia dari Sumatra hingga Papua. Monokultur sawit bukan hanya mengubah bentang alam; ia mengubah struktur kepemilikan, pola migrasi, dan hubungan sosial. Desa-desa yang dulu memiliki akses luas terhadap hutan kini bergantung pada satu komoditas global yang harganya fluktuatif.
Konflik agraria menjadi fenomena rutin, sementara hutan tropis yang selama jutaan tahun menjadi penyangga iklim mikro dan reservoir biodiversitas, menyerah pada logika produktivisme. Sawit telah menjadi apa yang disebut akademisi sebagai 'commodity frontier': kekuatan yang mendorong perubahan ruang hidup demi memenuhi kebutuhan pasar global. Namun di tingkat lokal, ia sering membawa kerentanan yang tak pernah masuk dalam neraca ekonomi nasional.
Ketika kerusakan telah terjadi, tahap berikutnya adalah ritual rehabilitasi, sebuah tahap yang dalam praktiknya lebih sering melahirkan ilusi ketimbang pemulihan ekologi. Banyak perusahaan menampilkan citra tanggung jawab lingkungan melalui proyek reklamasi, reforestasi, atau penataan pesisir. Tetapi penelitian di berbagai provinsi menunjukkan bahwa kegiatan ini sering dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban legal, bukan untuk memulihkan fungsi ekologis.
Dalam prakteknya, lubang tambang ditutup seadanya, hutan ditanami bibit cepat tumbuh yang tidak memiliki relevansi ekologis, pesisir dibentengi dengan struktur beton yang justru merusak dinamika alamiah. Ini bukan rehabilitasi, tetapi 'green washing' yang dibungkus dengan bahasa teknis dan foto drone beresolusi tinggi.
Lebih jauh, di era digital, kendali atas pengetahuan dan makna menjadi lebih penting daripada kendali atas lahan. Oligarki ekstraktif memahami betul hal ini. Karena itu mereka tidak hanya menguasai sumber daya fisik tetapi juga sumber daya simbolik: narasi pembangunan, kampanye tanggung jawab sosial, kemitraan strategis dengan akademisi, dan bahkan kerja sama dengan influencer lingkungan.
Publik kemudian disajikan gambaran yang menggembirakan tentang “tambang berkelanjutan”, “sawit ramah lingkungan”, atau “hilirisasi hijau”. Sementara itu, kritik struktural dipinggirkan dan dianggap sentimentil atau anti-pembangunan. Inilah hegemoni naratif yang membuat publik sulit membedakan antara informasi ilmiah dan strategi komunikasi korporasi.
Ironisnya, ketika memasuki musim politik elektoral, isu lingkungan muncul bak bintang tamu di panggung debat: dibicarakan seolah menjadi prioritas, padahal nyaris tak menyentuh instrumen kebijakan yang sesungguhnya menentukan nasib ekologi. Program lingkungan para kandidat jarang berangkat dari analisis ilmiah, apalagi dari pemahaman ekologi politik.
Mereka dibingkai sebagai gagasan normatif: penghijauan, daur ulang, rehabilitasi, digitalisasi pengawasan bukan sebagai transformasi struktural. Politik biaya tinggi membuat kandidat bergantung pada pendanaan dari sektor ekstraktif, sehingga agenda ekologis berubah menjadi permainan retorika yang aman secara finansial dan minimal secara substansi.
Di balik semua gejolak ekologis ini, masalah terbesar sebenarnya bersifat epistemologis: cara negara dan masyarakat melihat alam. Dalam paradigma pembangunan dominan, alam adalah “sumber daya”, sesuatu yang dapat dipetakan, dihitung, dievaluasi, dan direkayasa ulang. Pandangan ini tampak modern dan rasional, tetapi menyimpan dua ilusi berbahaya. Pertama, ilusi pertumbuhan tanpa batas, seolah hutan, sungai, tanah, dan pesisir dapat terus menanggung ekspansi ekonomi tanpa efek kumulatif.
Kedua, ilusi pemulihan instan, seolah ekosistem tropis yang kompleks, adaptif, dan saling terkait dapat dikembalikan ke kondisi semula hanya dengan proyek teknis atau kebijakan administratif. Kedua ilusi ini telah menjadi fondasi kebijakan publik Indonesia, sekaligus sumber kontradiksi struktural yang kini mulai terasa dampaknya.
Tetapi krisis ekologis bukannya tak terhindarkan. Literatur mutakhir di bidang tata kelola lingkungan, ekonomi regeneratif, dan transisi yang adil menawarkan berbagai pendekatan alternatif. Ekonomi regeneratif menolak logika kerusakan yang dibayar kemudian; ia mengusulkan pembangunan yang memperkuat, alih-alih mengikis, fungsi ekosistem.
Tata kelola polisentris yang dipopulerkan Elinor Ostrom, menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya tidak harus berpusat pada negara; komunitas adat, organisasi lokal, dan lembaga independen sering kali lebih efektif menjaga ekologi karena hubungan mereka dengan ruang bersifat langsung dan berjangka panjang.
Di Indonesia, praktik seperti sasi laut di Maluku, hutan adat di Kalimantan, atau subak di Bali menjadi contoh bahwa alternatif pengelolaan sudah ada, namun sering kalah oleh kekuatan finansial dan regulatif industri ekstraktif. Pada titik ini, yang diperlukan adalah keberanian politik dan epistemik untuk melepaskan diri dari cara pandang lama.
Indonesia membutuhkan tata kelola lingkungan yang tidak hanya teknis tetapi juga demokratis yang memungkinkan masyarakat lokal menentukan masa depan ruang hidup mereka. Indonesia meniscayakan kebijakan yang tidak sekadar membatasi kerusakan, tetapi memperkuat kapasitas ekosistem untuk beregenerasi. Kita memerlukan politik yang tidak sekadar memuja pertumbuhan, tetapi mampu membayangkan bentuk kesejahteraan yang tidak merusak fondasinya sendiri.
Krisis ekologis Indonesia tidak berkembang secara tiba-tiba; ia tumbuh dari pilihan-pilihan politik yang mensubordinasikan ekologi dan mengutamakan akumulasi. Namun arah sejarah dapat berubah. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa memperbaiki kerusakan, tetapi apakah ia mau mengubah struktur kekuasaan dan pengetahuan yang melanggengkan kerusakan itu.
Masa depan ekonomi mungkin dapat dinegosiasikan, tetapi masa depan ekologi tidak. Dan pada akhirnya, ekologilah yang akan menentukan apakah Indonesia dapat bertahan sebagai negeri yang tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga memiliki masa depan yang layak untuk dihuni.
Tulisan ini merupakan catatan atas diskusi, "Politik Ekstraksi dan Kerentanan Ekologis: Membaca Ulang Krisis Lingkungan Indonesia', Senen, 8/12/ 2025 kerjasama Indonesia Development Research dan STISNU Kota Tangerang.

(Penulis: Abdul Hakim, Pengajar Studi Perbandingan Politik, STISNU Kota Tangerang)