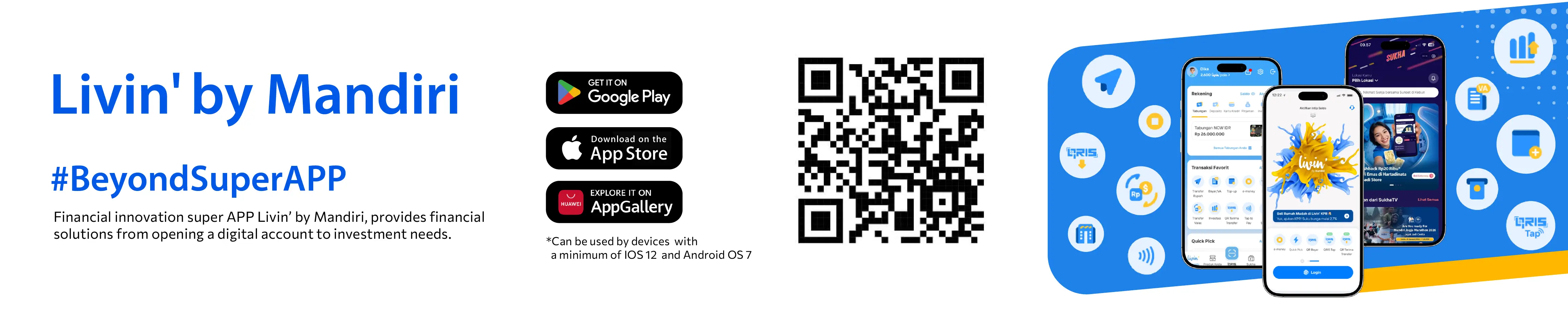Toxic Positivity: Ketika 'Bersyukur' Menjadi Racun Mental

Oleh Adel Gia Rastavarera - SMA Negeri 9 Yogyakarta
Juara II Kompetisi Menulis Cerita Anak Negeri 2024
ThePhrase.id - "Sudahlah, yang penting itu bersyukur." Lima kata sederhana yang sering kita dengar, tapi tahukah kamu? Kalimat penghibur ini justru bisa menjadi racun yang perlahan menggerogoti kesehatan mental seseorang. Seperti madu yang ternyata mengandung arsenik, kalimat-kalimat positif yang dipaksakan ini diam-diam membunuh validitas perasaan kita, terutama para remaja yang masih mencari jati diri.
Di era digital ini, media sosial dipenuhi dengan quotes motivasi dan status-status yang seolah meneriakkan "hidup harus selalu bahagia". Tapi tunggu dulu, apakah normal memaksakan senyum saat hati sedang remuk? Apakah wajar ketika seorang remaja yang mengalami anxiety attack justru dibalas dengan "coba deh dibawa happy aja"? Dalam budaya Indonesia yang mengutamakan harmoni, kita telah menciptakan generasi yang dipaksa untuk selalu terlihat baik-baik saja, bahkan ketika mereka sedang hancur di dalam.
The Phrase "Embrace your darkness to find your light" - sebuah paradoks yang justru lebih masuk akal dibanding paksaan untuk selalu berpikir positif. Toxic positivity, seperti yang didefinisikan Lukin (2019), adalah sebuah konsep yang memaksa kita untuk tetap positif sebagai satu-satunya jalan yang tepat dalam hidup.Cherry (2021) bahkan menegaskan bahwa ini adalah kepercayaan buta - tidak peduli seberapa mengerikan situasinya, seseorang harus tetap tersenyum dan berpikir positif. Bukankah ini terdengar seperti sebuah penjara mental yang dibalut dengan pita berwarna pink?
Mari kita bicara fakta, berdasarkan survei Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022, 34,9% atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Angka yang mencengangkan, bukan? Dan kamu tahu apa yang lebih mencengangkan? Sebagian besar dari mereka dipaksa untuk tetap bersyukur dan positive thinking tanpa diberi ruang untuk merasakan emosi yang sebenarnya.
Quintero & Long (2019) menjelaskan bahwa proses toxic positivity menghasilkan tiga hal berbahaya: penyangkalan, minimalisasi, dan invalidasi terhadap pengalaman emosi manusia yang sebenarnya. Bayangkan seorang remaja yang sedang mengalami depresi berat, dan yang dia dapatkan hanyalah "masih mending loh daripada yang lain" atau "coba deh banyak-banyak ibadah aja". Bukankah ini bentuk kekerasan emosional yang terselubung?
Lebih mengerikan lagi, penelitian Gross & Levenson (1997) membuktikan bahwa individu yang menekan emosinya, berpura-pura baik-baik saja, justru mengalami physiological arousal yang lebih signifikan. Detak jantung yang lebih kencang, kegelisahan yang meningkat, dan tekanan mental yang semakin dalam. Seperti bom waktu yang menunggu untuk meledak, hanya karena kita terlalu takut untuk mengakui bahwa "tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja".
Kita, bangsa Indonesia, memiliki kebiasaan unik yang sebenarnya cukup merusak. "Tidak enak ah kalau curhat", "Malu dilihat tetangga kalau ke psikolog", atau "Nanti dikira gila" - kalimat-kalimat yang sudah mendarah daging dalam konstruksi sosial kita. Budaya 'malu-malu' dan 'tidak enakan' ini secara tidak sadar telah menciptakan labirin toxic positivity yang membuat para remaja tersesat dalam kebingungan emosional mereka sendiri.
"Sudahlah, yang lain juga banyak yang lebih parah." Kalimat ini mungkin terdengar seperti penghiburan, tapi sebenarnya adalah bentuk mikro agresi yang merendahkan pengalaman seseorang. Dr. Jiemi Ardian menegaskan bahwa toxic positivity adalah bentuk generalisasi yang berlebihan terhadap keadaan bahagia, yang tujuannya justru untuk menyangkal penderitaan seseorang. Ini seperti memberikan plester untuk menutupi luka yang membutuhkan jahitan.
Bayangkan seorang remaja yang perlahan kehilangan suaranya sendiri. Bukan karena dia bisu, tapi karena toxic positivity telah mencuri kemampuannya untuk berkata "aku tidak baik-baik saja." Mengutip dari siloamhospitals.com, salah satu dampak paling mengerikan dari toxic positivity adalah kesulitan mengungkapkan emosi yang sebenarnya. Seperti sebuah pressure cooker yang terus diisi tanpa pernah dibuka katupnya.
Dalam fase pembentukan identitas yang krusial ini, toxic positivity menciptakan generasi yang sulit menjalin relasi tulus. Mereka terbiasa memalsukan perasaan, berpura-pura kuat, dan yang paling berbahaya - mengabaikan red flags dalam hubungan yang toxic dengan dalih ‘yang penting positive thinking’. Seperti yang dilaporkan dalam siloamhospitals.com, banyak remaja yang terjebak dalam abusive relationship karena terlalu terbiasa memaafkan dan berpikir optimis secara berlebihan.
Whitney Goodman, dalam bukunya "Toxic Positivity: Keeping It Real in a World Obsessed with Being Happy" mengatakan sesuatu yang mengejutkan: "Berlawanan dengan kepercayaan umum, tidak ada emosi negatif. Yang ada hanyalah emosi yang lebih sulit dialami atau yang menyebabkan lebih banyak tekanan bagi orang tertentu, dan semakin kamu menekan emosi tersebut, semakin sulit untuk mengelolanya." Ini bukan sekadar quotes untuk feed Instagram-mu. Ini adalah panggilan untuk bangun dari delusi toxic positivity yang telah kita normalisasi.
Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulailah dengan mengakui bahwa setiap emosi valid. Ketika seorang teman curhat, berhenti mengatakan "yang sabar ya" atau "berdoa aja". Ganti dengan "Aku dengar kamu" atau "Ceritakan lebih banyak". Validasi adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus - bukan pemaksaan untuk selalu terlihat bahagia. Beri ruang untuk mereka menangis, marah, atau bahkan hanya diam. Karena terkadang, kehadiran tanpa judgement adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan.
Kedua, mulailah membangun komunitas yang aman. Ciptakan ruang di mana kamu dan teman-temanmu bisa berbagi tanpa takut dihakimi. Bicarakan tentang kecemasan menghadapi ujian tanpa harus ditutup-tutupi dengan "santai aja". Diskusikan tentang tekanan orang tua tanpa harus diakhiri dengan "masih mending". Karena healing yang sejati dimulai ketika kita berani membuka topeng dan menunjukkan wajah asli kita.
Yang terakhir, dan mungkin yang terpenting - berani mencari bantuan profesional. Toxic positivity telah menciptakan stigma bahwa ke psikolog adalah tanda kelemahan. Padahal justru sebaliknya - mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah bentuk keberanian tertinggi. Seperti tubuh yang perlu check up rutin, mental kita juga perlu perawatan profesional. Ini bukan tentang seberapa parah masalahmu, tapi tentang seberapa serius kamu menghargai kesehatan mentalmu.
Untuk para remaja yang sedang membaca ini, kamu tidak perlu menjadi matahari yang selalu bersinar. Terkadang, kamu bisa menjadi bulan yang hanya memantulkan cahaya. Bahkan, kamu bisa menjadi langit mendung yang perlu menumpahkan hujan. Semuanya normal, semuanya manusiawi. Jangan biarkan toxic positivity mencuri hakmu untuk merasakan spektrum emosi secara penuh. Karena pada akhirnya, kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada kenyamanan orang lain yang tidak bisa menerima ketidaksempurnaanmu.
Dan untuk kita semua, sudah saatnya mengubah narasi. Berhenti menjadikan "bersyukur" sebagai band-aid untuk luka yang membutuhkan jahitan. Berhenti menjadikan kesehatan mental sebagai hal yang tabu. Karena pada akhirnya, generasi yang berani mengakui kelemahannya adalah generasi yang benar-benar kuat. Mereka yang berani menghadapi kegelapan dalam dirinya, justru akan menemukan cahaya yang lebih terang dari sekedar topeng positif yang dipaksakan.